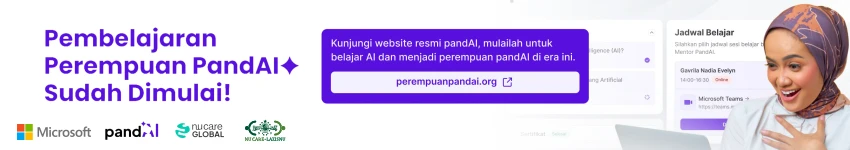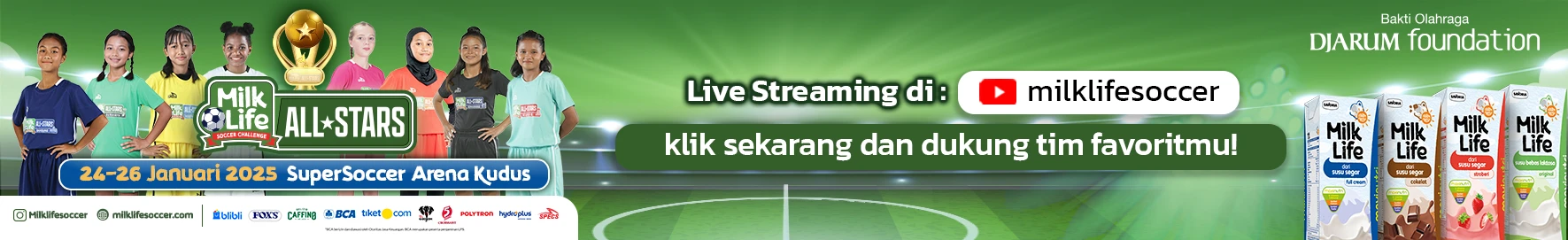Oleh Muhammad Negar Zafarani
Melihat hubungan pesantren dan keraton, terutama di Yogyakarta dan Solo, seperti melihat dua saudara yang sudah tidak saling kenal. Seakan keduanya saling menegasikan kekerabatan dekat di antara mereka. Keduanya menerima ‘bentukan’ (invensi) bahwa satu-satunya fakta di antara mereka adalah kontestasi politik, ekonomi, sosial, dan agama (dalam hal ini Islam). Di antara mereka tumbuh suatu anggapan umum: sulit membuktikan bahwa mereka berasal dari jalur geneologis yang sama.
Bagi kalangan pesantren di Yogyakarta misalnya, hubungan kekerabatan antara para penguasa Jawa dengan ulama dikaitkan dengan pendiri Desa Mlangi, di daerah Mlati, Sleman, Yogyakarta, yaitu Raden Mas Sandiyo, seorang pangeran dari Keraton Surakarta pada abad 18 Masehi yang menepi dari sengkarut kekuasaan di dalam keraton. Sang pangeran tidak lain adalah kakak sulung dari Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maupun Pakubuwana III yang saat itu bertahta di Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebagian besar pesantren dan ulama di sekitar Yogyakarta adalah turunan langsung dari Raden Mas Sandiyo yang nantinya lebih dikenal dengan nama Mbah Nur Iman.
Tapi kalau sosok Mbah Nur Iman ditanyakan kepada pihak Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maka sosok ini tidak lebih dari seorang ulama yang ditunjuk oleh penguasa pada masanya. Keraton selalu menempatkan diri sebagai sentra dari segala bentuk kekuasaan dan otoritas, termasuk otoritas keagamaan dan keislaman. Pesantren-pesantren dianggap sebagai salah satu sekrup dari rangkaian kompleks kekuasaan dari keraton. Gamblangnya, tidak pernah ada pengakuan terbuka dari keraton akan hubungan kekerabatan langsung mereka dengan kalangan pesantren. Mereka ‘gengsi’ mengakui hubungan geneologis dengan kalangan ulama di pesantren.
Mungkin karena pertimbangan dan andaian akan adanya kekerabatan antara mereka dengan para penguasa Jawa, kiai-kiai di Yogyakarta dan keluarganya sering kali memilih politik akomodatif terhadap penguasa Jawa, Keraton Yogyakarta maupun Puri Pakualaman. Setiap terjadi sengkarut atau konflik di internal keraton, atau pun konflik keraton dengan masyarakat Yogyakarta, para kiai menjalankan politik diam. Hal itu kemudian ditambahi dengan argumen politik Sunni (Ahlusunnah wal-Jamaah) yang terkenal sangat lentur, bahwa Sultan dan Paku Alam adalah para penguasa muslim yang harus diikuti oleh umat Islam walaupun mereka pemimpin (ulil amri) yang tidak ideal.
Doktrin politik Sunni dalam Islam tidak harus dipahami secara datar dan sempit. Politik diam yang dijalankan para ulama pesantren dalam persoalan politik keraton tidak selamanya negatif, tetapi sering kali sebagai tindakan untuk merangkul semua kelompok yang terlibat di dalam konflik kekuasaan untuk menghindari berbagai potensi pembelahan di tengah masyarakat, khususnya dampak konflik politik tersebut terhadap masyarakat bawah. Politik diam acap kali adalah tindakan negosiasi untuk memilah hal-hal mendasar dan mengambil keputusan yang lebih ringan resikonya bagi kemaslahatan umat.
Berbeda dengan Jawa Timur dan daerah Pantura di utara Jawa Tengah: dua basis kaum santri di tanah Jawa, mereka melihat diri mereka adalah anti-tesa dari keraton-keraton Jawa di Yogyakarta dan Solo. Mereka merasa sebagai pewaris geneologis para Wali Jawa yang sering kali bertentangan dengan para penguasa Mataram Islam. Sejarah perlawanan Kiai Ahmad Mutamakkin di Desa Cebolek misalnya, dianggap sebagai penggalan kisah resistansi kalangan pesantren terhadap hegemoni penguasa pedalaman Jawa. Umumnya, orang Pantura merasa tidak mengenal kultur Jawa yang adiluhung dan bertingkap. Mereka merasa lebih egaliter sesuai dengan ajaran para Wali dan Syeikh Siti Jenar. Mereka merasa sebagai orang Jawa yang jauh dari segala aksesori feodalisme Jawa di pedalaman. Mereka tidak mengenal literasi Jawa seperti hierarki bahasa dan pergelaran wayang. Orang Pantura merasa tidak memiliki perikatan apapun dengan segala mitologi penguat dari kekuasaan keraton Jawa pedalaman seperti Nyi Roro Kidul. Justru hal-hal yang terkait dengan petaka dan bala dalam kehidupan dikaitkan dengan segala citra dan simbol dalam kekuasaan Jawa pedalaman.
Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Apakah tidak ada bukti-bukti faktual tentang keterhubungan antara pesantren dan keraton? Bukankah dinasti Kesultanan Mataram Islam yang didirikan di alas (belantara) Mentaok (nama masa lalu dari Yogyakarta) adalah strategi politik lanjutan dari para penguasa muslim di Pantura, Kesultanan Demak yang didukung sepenuhnya oleh para Wali? Bukanlah Kesulatanan Pajang di Pengging (sekarang masuk administrasi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah) adalah kesultanan yang nantinya melahirkan para sultan di Kesultanan Mataram Islam dan para ulama di pesantren? Bukankah Sunan Kali Jaga terlibat aktif sebagai peletak dasar Kesultanan Mataram Islam?
Sebagai sebuah isu yang kompleks, hubungan antara pesantren dan keraton di Yogyakarta dan Solo sebaiknya dilihat secara lebih terbuka. Artinya, kedua entitas ini sebaiknya diletakkan dalam konteks “keduniawiahannya”. Artinya, keduanya tetaplah entitas historis yang kalis oleh kehidupan nyata. Pesantren maupun keraton tidak bebas dari anasir-anasir pembentukan kolonialitas yang jauh lebih besar di masa lalu maupun di masa sekarang. Pesantren hari ini tidak seideal pesantren di masa lalu, seperti halnya keraton hari ini tidak seideal gambaran keraton di masa lalu. Hukum yang berlaku adalah dinamika: proses negosiasi dengan kenyataan riil untuk mengembangkan tradisi.
Satu-satunya kajian akademik yang pernah membahas tentang “perpisahan” dua saudara kandung; pesantren dan keraton, adalah kajian yang dilakukan oleh Nancy K Florida, seorang antropolog dari Cornell University, Amerika Serikat. Di bagian awal bukunya yang berbasis pada riset disertasinya, Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang: Sejarah sebagai Nubuat di Jawa Masa Kolonial, Florida menggambarkan kekerabatan pesantren dan Keraton Mataram Islam sampai kemudian terjadi proses pembelahan sosial-politik-budaya yang dilakukan kaum kolonial Belanda seiring dengan menguatnya kolonialisasi pada abad ke-19 Masehi. Penelitian luas ini kemudian disingkat oleh Florida dalam sebuah artikelnya, Pada Tembok Keraton Ada Pintu: Unsur Santri dalam Dunia Kepujanggan “Klasik” di Keraton Surakarta.
Florida menjelaskan ambivalensi kaum kolonial Belanda terhadap Islam di Jawa: Islam adalah sesuatu yang menakutkan, mencurigakan, dan mengancam. Ancaman “Islam fanatis” (istilah Orientalis) bisa berkecambah di mana-mana. Pada sisi lain, mereka berhasrat membuang “penampakan” Islam di Jawa dari alam kesadaran masyarakat Jawa dengan cara mengembangkan gambaran tentang Islamnya orang sebagai Islam yang tidak benar; bagi orang Jawa yang benar, Islam adalah sesuatu yang asing dan merusak kejawaan; dan singkatnya, Islamnya orang Jawa adalah Islam yang sinkretik.
Guna mempercepat proses pembentukan (invensi) Islam –sinkretik itu, demikian Florida, dibentuklah enklave sosial lain yang lebih ideal dalam imajinasi Jawa kolonial, yakni enklave sosial para elite Jawa, para priyayi, yang kejawaaannya berbeda dari kejawaan orang-orang Jawa di pedesaan. Para elite dibentuk menjadi ‘cagar kejawaan’ yang esensial dan tidak kotor oleh anasir asing seperti Islam. Persis di titik inilah terjadi pemisahan pesantren dan keraton.
Florida menengarai, penemuan kaum kolonial Belanda akan Islam-sinkretik dikembangkan secara intensif karena trauma mereka akibat Perang Jawa (1825-1830). Berbeda dengan para peneliti asing lainnya, Florida melihat hubungan intim, bukan semata kolaboratif, antara penguasa Jawa dengan kiai-kiai pesantren dalam mengobarkan perlawan fisik yang paling menggetarkan dalam sejarah kolonial Belanda di Jawa.
Tulisan saudara Muhammad Ishom, dosen Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta,
Sultan HB X dan Calon Suksesornya yang Perempuan, yang dimuat
NU Online pada Ahad, 28 Juli 2019 seharusnya melihat kompleksitas hubungan pesantren dan keraton. Tulisan tersebut seharusnya peka juga dengan beragam sikap kalangan pesantren terkait isu suksesi di Karaton Yogyakarta Hadiningrat. Tidak sedikit kalangan pesantren di Yogyakarta menolak dengan tegas penunjukkan Gusti Pembayun sebagai calon pengganti ayahnya, Sultan Hamangkubuwono X.
Oleh mereka yang kontra sabda raja, penunjukkan Gusti Pembayun ini dianggap sebagai pelanggaran paugeran yang berlaku dalam tradisi Kesultanan Mataram, dan khususnya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Bahkan tidak sekedar paugeran, penunjukan tersebut dianggap sebagai pemutusan sendi-sendi Islam Nusantara; semacam perusakan terhadap tradisi keislaman yang telah diletakkan oleh para Wali tanah Jawa.
Secara umum harus dikatakan, penunjukan putri mahkota oleh HB X tidak bisa dengan gegabah dianggap sebagai lompatan sikap progresif seorang Raja Jawa dalam memandang keagungan seorang perempuan. Penunjukan sang putri tidak terkait sama sekali dengan semangat kesetaraan gender atau feminisme tetapi penunjukan tersebut harus dipahami dalam konteks “keduniawiahan” yang dialami oleh keluarga sultan dan lembaga keraton secara umum di tengah kepungan perubahan kekuasaan: modal dan negara.
Melihat beragamnya penyikapan kalangan pesantren, Nahdlatul Ulama, terhadap dinamika kekuasaan yang berkembang di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, maka persoalan ini harus dilihat dengan latar belakang yang lebih luas, tidak datar dan hitam putih. Sikap para Nahdliyin yang kontra-Sabda Raja juga harus dipahami sebagai kepedulian seorang saudara dalam merawat tinggalan para Wali Jawa. Wal-Allahu yahdi ilaal haqqi.
Penulis adalah pengarang buku “Aspek-Aspek Sekular Tradisi Tarekat di Pesantren Indonesia” (2017).