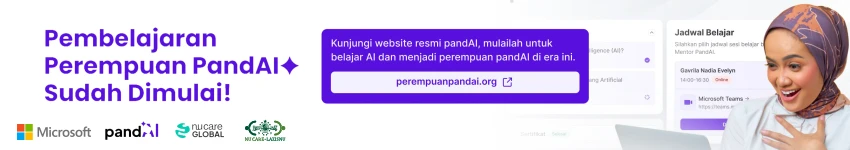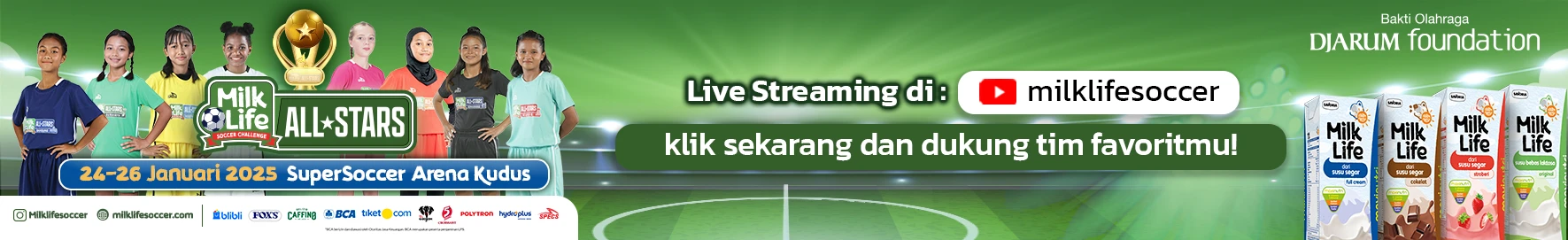Oleh Muhammad Muhibbuddin*
Tragedi kekerasan pendidikan kini terulang lagi. Cliff Muntu (19) mahasiswa praja tingkat II Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor Jabar kini telah meninggal secara misterius. Kematian mahasiswa asal Manado Sulawesi Utara ini diduga akibat penganiayaan oleh seniornya sendiri.
Kasus-kasus seperti ini di IPDN, sebenarnya bukan kali ini saja. Sejak 1990 hingga 2004 setidaknya terjadi 35 penganiayaan berat yang berakibat pada kematian (Kompas: 4/4/2007). Penyebabnya rata-rata adalah sama yakni akibat aksi kekerasan yang terjadi antara senior terhadap yuniornya. Penyebab meninggalnya Cliff Muntu yang misterius ini juga diduga sama. Kekerasan yang terjadi dikalangan senior dan yunior IPDN ini biasanya terkait dengan tata tertib atau peraturan dan organisasi kampus. Dengan alasan untuk menjaga dan menegakkan peraturan itulah seringkali aksi kekerasan (violance) dijadikan instrumen. Hal ini seperti yang dialami oleh Wahyu Hidayat pada 2004 yang lalu ketika kampus ini masih bernama STPDN.gt;
Kalau memang benar kematian Cliff terkait dengan penegakan kedisiplinan berarti semakin menegaskan bahwa penegakan hukum atau aturan di IPDN selalu identik dengan kekerasan. Padahal sebenarnya keduanya mempunyai definisi dan orientasi yang berbeda. Semangat hukum adalah semangat untuk melindungi manusia dari ketakutan dan kerusakan. Sementara kekerasan, secara terminologis, berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang(Kamus besar Bahsa Indonesia, 425:19878). Jelas kedua hal tersebut bukan hanya berbeda tapi justru berlawanan.
Namun untuk mengetahui lebih jauh, kita tidak cukup mengetahui kekerasan dari aspek definisinya saja, melainkan juga motif-motif atau tipe -tipenya. Karena tipologi kekerasan yang ada, termasuk kekerasan di IPDN ini berlainan dengan yang lainnya. Menurut Abdul Qadir Saleh(2003) membagi tipologi kekerasan ada tiga yaitu: pertama, kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. Tipologi ini dilatar belakangi oleh pendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. Kedua , kekerasan sebagai produk dari struktur, yakni kekerasan yang, sebagaimana diistilahkan oleh Johan Galtung sebagai kekerasan yang tidak langsung, statis dan memperlihatkan stabilitas tertentu. Kekerasan model ini sering dilakuakn oleh sebuah struktur social seperti negara. Sementara yang ketiga, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan pelaku. Yakni kekerasan sebagai jejaring antara aktor atau pelaku dengan struktur.
Berdasarkan klasifikasi di atas, Kekerasan yang dilakukan oleh para senior mahasiswa IPDN terhadap Cliff ini termasuk kategori pertama. Karena kekerasan ini merupakan manifestesi dari aktor atau kelompok aktor IPDN yang secara geneologis menjadi budaya para senior IPDN. Dalam konteks kriminalitas, kekerasan ini sudah termasuk tingkat kejahatan tingkat tinggi (extra-ordinary crime). Karena kekerasan ini bukan hanya menyebabkan luka fisik namun telah melenyapkan nyawa Cliff. Maka ini termasuk tingkat kekerasan yang sangat tidak manusiawi meskipun itu berpretensi untuk kebaikan seperti menegakkan peraturan.
Sementara itu secara moralitas ini sungguh naif. Karena aksi kekerasan ini justru terjadi di lembaga pendidikan. Lemabaga pendidikankan apapun, terutama kampus perguruan tinggi, adalah salah satu lembaga yang menjadi simbol perjuangan dan tegaknya nilai-nilai humanmisme, idealisme, dan moralitas.
Namun ternyata dalam praktiknya sebagaian lembaga pendidikan justru lebih menanamkan nilai-nilai kekerasan dan anarkisme terhadap mahasiswanya.Dalam hal ini kampus bukan lagi menjadi persemaian intelektual yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tapi berbalik menjadi ajang penggodokan “algojo-algojo kampus” yang kejam ,ganas, biadab dan bar-bar.
Dalam tragedi ini ada benarnya anggapan Thomas Hobbes, bahwa satu sisi manusia adalah srigala bagi yang lain (homo homini lupus). Manusia terhadap yang lainnya bukan menjadi seorang kawan atau saudara yang siap menyayangi dan mencintai, namun justru menjadi predator bagi yang lainnya. Namu apabila ini dipraktikkan oleh manusia-manusia akademik yang akrab dengan ilmu pengetahuan adalah sungguh naif. Karena menurut Plato, kebijaksanaan adalah pengetahuan. Dengan ini berarti bahwa seorang yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan idealnya harus mempunyai sifat bijaksana, semakin tinggi pengetahuannya semakin tinggi pula Kebijaksanaannya.
Sifat-sifat keras, garang, ganas, anarkis, bara-bar dsb adalah ciri sifat-sifat orang yang tidak berpendidikan, primitif dan katrok. Kalaupun tujuannya untuk menegakkan supremasi atau kewibawaan hukum dan tata tertib, hal itu tetap harus dilakukan dengan semangat humanisme dan etis. Tujuan ditegakkannya hukum atau tata tertib diantaranya adalah untuk melindungi hak-hak manusia, termasuk hak hidup. Maka sangat konyol apabila ingin menegakkan hukum atau peraturan, tata tertib dsb justru mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini namanya justru aksi premanisme yang jelas bertentangan dengan hukum.
Maka supaya premanisme kampus ini tidak menjadi budaya dilembaga pendidikan, khususnya di IPDN segala bentuk kedisiplinan yang mengarah pada tindakan kekerasan harus dmusnahkan. Aksi militerisme, yang merupakan aksi kesewenang-wenangan para senior terhadap yunior, para atasan terhadap bawahan, para dosen terhadap mahasiswa harus dihentikan. Akan lebih baiknya kalau pelaksanaan kedisiplinan atau kepatuhan terhadap sebuah peraturan didasarkan pada aspek kedewasaan dan kesadaran, atau meminjam istilahnya Sigmund Freud pada aspek superego. Artinya setiap civitas akademika dibiasakan untuk sadar dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri.
Begitu juga dalam masalah aturan atau tata tertib yang mengatur tata hubungan dan komunikasi antar semua civitas dalam kehidupan sehari-hari Juga harus dievaluasi kembali. Sebab tidak semua undang-undang ,hukum, tata tertib dan sejenisnya mempunyai semangat memanusiakan manuisa. Menurut Aristoteles sendiri aturan telah terbagi menjadi tiga: yang pertama, aturan despotik, yakni aturannya paratUran, kedua, aturan konstitusional, yakni peraturan yang diberlakukan dikalangan yang setara, yang ketiga, aturan royal, yakni peraturan monarki yang bijak. Dalam hal ini peraturan yang despotik adalah jelas peraturan yang tidak memanusiakan manusia. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang membolehklan seorang senior untuk menghukum secara fisik terhadap yuniornya secara berlebihan. Maka peraturan semacam ini harus ditinggalkan dan diganti dengan peraturan yang konstitusional atau minimal yang royal.
Satu lagi, faktor lain yang juga tidak boleh dilupakan adalah membekali mahasiswa dengan ilmu-ilmu yang sarat niliai-nilai kerohanian seperti seni, sastra, filsafat, tasawuf, dan sejenisnya. Hal ini untuk melunakkan dan menghaluskan perasaan mahasiswa terhadap sesamanya. Selama ini mahasiswa, khususnya IPDN, hanya dibekali ilmu-ilmu yang berorientasi fisik belaka. Dengan sistem dan paradigma keilmuan yang demikian ini hati dan kesadaran seorang mahasiswa sama sekali tidak terasah. Pada akhirnya mahasiswa hanya diperodak menjadi komputer atau robot yang selalu patuh dan dikendalikan oleh formalitas sistem. Persoalan apapun pendekatannya selalu hitam putih yang sifatnya sangat dangkal.
Hal semacam itulah yang saat ini harus disadari oleh pihak semua warga akademik termasuk IPDN. Para akademisi, khususnya akademisi IPDN harus sadar bahwa sekolah atau kampus adalah tempat kawah candra dimuka untuk mencetak manusia -manusia yang berilmu supaya lebih sempurna kualitas kemanusiaannya, bukan untuk mengkader manusia-manuisa menjadi preman. Oleh karena itu aksi premanisme pendidikan harus segera dikubur.
Penulis adalah Staf Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan Aktivis Jaringan Islam Kultural (JIK)
Terpopuler
1
Fantasi Sedarah, Psikiater Jelaskan Faktor Penyebab dan Penanganannya
2
Khutbah Jumat: Lima Ibadah Sosial yang Dirindukan Surga
3
Pergunu Buka Pendaftaran Beasiswa Kuliah di Universitas KH Abdul Chalim Tahun Ajaran 2025
4
Pakai Celana Dalam saat Ihram Wajib Bayar Dam
5
Kabar Duka: Ibrahim Sjarief, Suami Jurnalis Senior Najwa Shihab Meninggal Dunia
6
Ribuan Ojol Gelar Aksi, Ini Tuntutan Mereka ke Pemerintah dan Aplikator
Terkini
Lihat Semua